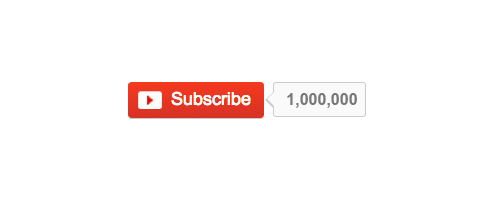“Setiap
tempat bersimbah darah dan kanal-kanal dipenuhi dengan mayat-mayat. Sebagian
besar kota diselimuti abu dan lima ribu warga Cina yang terkenal rajin dan
penuh pengabdian itu telah tewas.” Demikian kisah memilukan dari sebuah catatan
akhir abad ke-18 yang pernah tersimpan di perkumpulan komunitas Cina di
Jakarta.
Sebuah kota membutuhkan warga yang menghidupkan kegiatan
perekonomian. Salah satu komunitas perintis yang bermukim di dalam tembok kota
adalah masyarakat Cina yang kelak menjadi cikal bakal budaya peranakan di kota
itu. Bahkan, VOC menunjuk seorang kapitan pertama untuk mengatur
masyarakat Cina di Batavia pada awal abad ke-17.
Pada awal abad ke-18 perekonomian dunia yang melesu dengan
turunnya harga gula turut mempengaruhi kehidupan Batavia. Pengangguran di
Batavia meningkat, sementara itu pendatang dari Cina kian memadati kota tertua
di Asia Tenggara itu. Setidaknya 4.000 orang Cina bermukim di dalam tembok
kota, sedangkan sekitar 10.000 orang berada di luar tembok kota.
Gubernur Jenderal VOC—Kongsi Dagang Hindia Timur— Adriaan
Valckenier, melakukan kebijakan untuk mengirimkan kelebihan pengangguran itu ke
Sri Langka karena di pulau tenggara India itu VOC juga mendirikan benteng dan
kota persinggahan. Namun, terdapat desas-desus yang berkembang di Batavia bahwa
orang-orang Cina yang dikirim dengan kapal ke Sri Langka itu dibunuh dengan
menceburkan mereka ke laut lepas.
Komunitas Cina di pinggiran Batavia mulai resah dan mengancam
untuk melakukan pemberontakan di kota. Mereka juga mendapat dukungan dari warga
Cina dalam tembok kota, melengkapi diri dengan berbagai senjata. Di beberapa
tempat, seperti Meester Cornelis—kini Jatinegara—telah dikuasai pemberontak
Cina.
Pada 9 Oktober 1740, terjadilah huru hara di dalam tembok Kota
Batavia. Para serdadu VOC melakukan perampokan dan pembersihan warga Cina.
Permukiman Cina dibakar. Semua warga Cina dalam tembok kota, baik pria, maupun
wanita, bahkan anak-anak yang lari berhamburan ke jalanan kota itu dibunuh
dengan keji.
Bahkan, beberapa ratus orang Cina yang menjadi
tahanan di Stadhuis—Balai Kota Batavia, kini Museum Sejarah
Jakarta—dibebaskan, lalu disembelih di halaman belakang gedung itu.
Diperkirakan antara 5.000 sampai 10.000 warga Cina telah dibantai. Rumah
Kapitan Cina Ni Hoe Kong yang terletak di Roa Malaka—nama jalan itu masih ada
hingga kini—dijarah dan dihancurkan. Sang Kapitan yang bertanggung jawab
terhadap segala aktivitas orang-orang cina itu ditangkap dan akhirnya wafat
dalam pembuangannya di Ambon.
Polemik
kian membesar, bahkan turut melibatkan kalangan lokal setelah beredar isu bahwa
orang-orang Cina berencana memperkosa perempuan lokal, membunuh para lelakinya,
atau menjadikannya sebagai budak (Setiono, 2008:114). Maka, kaum pribumi dari
berbagai suku yang ada di Batavia pun bergabung dengan VOC untuk membantai
etnis Tionghoa. Valckenier memanfaatkan situasi ini dengan menggelar sayembara.
Ia menjajikan hadiah besar untuk setiap kepala orang Cina yang berhasil
dipancung (Hembing Wijayakusuma, Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah
Angke, 2005:103).
Dampaknya
signifikan. Ratusan orang Cina ditangkap dan disembelih di halaman Balai Kota
Batavia, termasuk para tahanan. Pembantaian berlangsung setidaknya hingga 22
Oktober 1740, belum termasuk rangkaian upaya pembersihan setelahnya. Tidak
kurang dari 10 ribu orang Cina tewas, dan 500 orang lainnya luka berat, juga
lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar baik oleh serdadu VOC
maupun kaum pribumi (W.R. van Hoevell, Batavia in 1740, 1840:447-557).
Aksi berdarah yang mirip genosida alias pemusnahan etnis ini kemudian dikenal dengan istilah Chinezenmoord (Pembunuhan Orang Tionghoa), selain Geger Pacinan atau Tragedi Angke dalam ungkapan lokalnya. Angke sendiri konon berasal dari dua kata dalam bahasa Hokkian: ang yang artinya “merah” dan ke yang berarti “sungai” (Alwi Shahab, Betawi: Queen of the East, 2002:103). Dengan demikian, "angke” dapat diartikan “sungai merah”, semerah banjir darah kaum Tionghoa yang dibantai di Batavia pada 1740 itu.
Seorang pelaku pembantaian dan perampokan, G. Bernhard Schwarzen, berkisah dalam bukunya Reise in Ost-Indien yang terbit pada 1751. Ironisnya, dia juga membunuh orang Cina yang dia kenal baik dan kerap mengundangnya makan malam. Menurutnya, baru empat hari kemudian pembantaian berhenti. Tak tersisa lagi orang Cina di dalam tembok kota. “Seluruh jalanan dan gang-gang dipenuhi mayat, kanal penuh dengan mayat,” tulisnya. “Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu.”
Dua tahun kemudian, Gubernur Jenderal Valckenier yang dianggap
bertanggung jawab atas tragedi di Batavia, dijatuhi hukuman penjara di Kastil
Batavia selama 9,5 tahun sebelum akhirnya meninggal dan dimakamkan tanpa
upacara.
Menurut Mona Lohanda, pemerhati sejarah peranakan Cina dan
penulis buku Sejarah Para Pembesar
Mengatur Batavia, kerusuhan 1740 meluas hingga ke Jawa. Bahwa
tragedi orang-orang Cina bukan hanya berdampak kepada kehidupan di Batavia,
tetapi juga berakibat pada ketidakstabilan politik di Kasultanan Mataram.
Bagaimana peristiwa itu meluas hingga ke Jawa? Dampak tragedi
Oktober 1740, telah membuat Kasultanan Banten bersiaga dengan tiga ribu
prajuritnya untuk menghadang orang-orang Cina yang melarikan diri dari Batavia.
Gagal memasuki Banten, para pelarian itu bergerak ke timur. Sejumlah seribu
orang bertemu di pantai sisi utara Pati, kota kecil di Jawa Tengah. Akhirnya,
sebagai tindakan balasan, mereka bergabung dengan komunitas Cina asal Semarang
dan mengepung benteng VOC di kota itu. Tak hanya itu, mereka juga menyerang
pertahanan VOC di Rembang, sebuah benteng pinggir pantai. Tampaknya, inilah
perlawanan terhebat dan terheroik orang-orang Cina kepada VOC dalam
sejarah peranakan Indonesia yang terlupakan.
Jikalau Raja Kartasura, Susuhunan Pakubuwana II, menyatukan
antara kekuatan pemberontakan orang-orang Cina dan kekuatan prajurit
keratonnya, mungkin saja VOC bisa hengkang dari Jawa Tengah. Namun, sang raja
tampaknya menyia-nyiakan momentum sehingga VOC berhasil menguasai keadaan
dengan campur tangan dalam urusan kerajaan. Meskipun konspirasi Cina-Jawa dalam
“Geger Pacinan” dapat dipatahkan VOC, perseteruan keluarga itu baru berakhir
pada 1755 dengan terbaginya Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan
Yogyakarta.
Usai tragedi kebiadaban itu, tidak ada warga Cina yang kembali
ke Batavia. Lalu, VOC memberikan izin tinggal bagi orang-orang Cina di sebelah
selatan tembok kota, daerah ladang tebu dan berawa milik Arya Glitok, seorang
adiwangsa asal Bali. Kelak, pecinan baru itu dikenal dengan sebutan mirip nama
belakang bekas pemiliknya: Glodok. Inilah salah satu cerita paling berdarah, juga
perih, dalam sejarah Nusantara.
Referensi
:
nationalgeographic.grid.id
tirto.id








.jpg)